Sepucuk Surat dari Yokohama untuk Remy Sylado
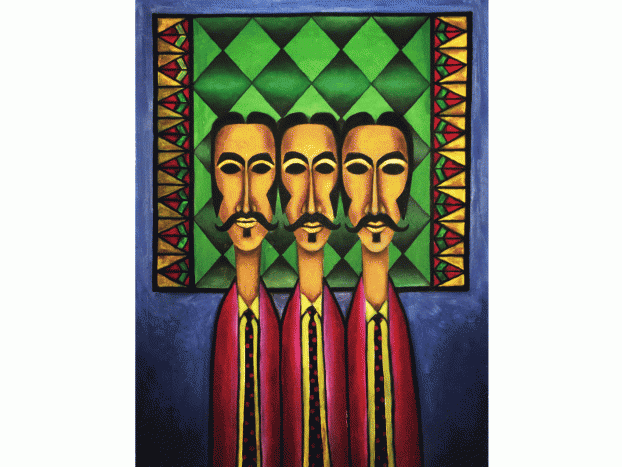
DARI depan pintu masuk utama rumahnya, sastrawan Remy Sylado, 77, berteriak kecil seakan hendak meminta sesuatu. Samar-samar suaranya terdengar dan tak begitu jelas di telinga ini.
Buru-buru dari arah dapur, Marie Louise Tambayong, istri terkasih Remy, melangkah ke kamar. Ia memalingkan kepala dan melotot ke ranjang tidur, tempat sehari-hari Remy gunakan untuk berbaring dan berselonjor.
“Ada apa, Pi (papi)?” ujar Emmy, sapaan Marie. “Minum,” jawab Remy seraya matanya menerawang ke langit-langit kamar. “Bentar ya,” sambung Emmy sejenak, lalu melangkah ke dapur yang hanya berjarak lima langkah.
Sepekan kemarin, saya bertandang kembali ke rumah Remy di bilangan Cipinang, Jakarta Timur, untuk kesekian kalinya. Saya sengaja tidak mengabarkan kedatangan kali ini agar lebih santai.
Tiga roti balok keju plus coklat saya tenteng dari rumah dan serahkan kepada Emmy. Oleh-oleh sudah disiapkan sebelum berkunjung ke rumah sang maestro tersebut. “Hanya ada roti saja. Tidak bawa apa-apa, Tante Emmy,” ujar saya. “Tidak apa-apa. Remy suka sekali roti,” sambung Emmy, ramah.
Sejurus, mata Remy melirik sayu ke arah saya. Ia sudah lebih segar dari sebelum-sebelumnya. Meski demikian, ia belum bisa mengangkat badannya untuk duduk atau bangun secara normal. Ia hanya terbujur dan terlentang di tempat tidur.
Kami bercerita dari hati ke hati. Mula-mula tentang topik perkembangan puisi pascakontemporer, tokoh baru peraih Nobel Prize, sampai topik perfilman terbaru yang menghiasi bioskop. “Siapa peraih terakhir (nobel)?” tanya Remy perlahan-lahan. “Abdulrazak Gurnah, sastrawan dari Tanzania, tapi ia sudah lama di Eropa,” ucap saya. “Hebat!” cetus dia, singkat.
Memang, nama Gurnah menjadi perbincangan menarik sejak ia menerima hadiah paling bergengsi di panggung sastra dunia tersebut. Karya-karyanya masih menjadi bahan diskusi di berbagai perguruan tinggi hingga hari ini.
Pada 7 Oktober 2021, ia dianugerahi Hadiah Nobel Sastra atas penetrasi tanpa kompromi dan welas asihnya terhadap efek kolonialisme sekaligus nasib pengungsi di jurang antara budaya dan benua.
Gurnah adalah novelis kulit hitam pertama yang menerima hadiah tersebut sejak 1993, ketika Toni Morrison memenangkannya dan penulis Afrika pertama sejak 2007, ketika Doris Lessing menjadi penerimanya.
Mau tak mau, Indonesia memang masih belum begitu menjadi “prioritas” di bidang sastra. Namun bukan berarti kita tidak memiliki nama-nama hebat. Sebut saja Pramoedya Ananta Toer yang pernah diusulkan. Sayang, belum berhasil saja.
Keberhasilan Gurnah memang menjadi inspirasi bagi para penulis Afrika. Novelnya By the Sea adalah sebuah karya yang menginspirasi. Pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat oleh The New Press pada 11 Juni 2001 dan di Inggris oleh Bloomsbury Publishing pada Mei 2001.
Ini adalah novel keenam Gurnah sebelum menerima nobel. By The Sea masuk daftar panjang untuk Booker Prize dan terpilih untuk Los Angeles Times Book Prize. Banyak kritikus menaruh simpati pada bukunya.
By the Sea mengisahkan seorang bernama Saleh Omar. Ia mencoba memasuki Inggris dengan paspor palsu. Omar juga menggunakan nama samaran "Rajab Shaaban Mahmud", identitas yang dia curi untuk digunakan pada paspor palsunya.
Novel ini juga menarasikan Latif Mahmud, putra Rajab Shaaban Mahmud yang asli, seorang pria yang ternyata adalah bajingan. Latif Mahmud juga melakukan perjalanan ke Eropa, tetapi dengan rute yang lebih sah—mendapatkan visa pelajar ke Jerman Timur dan bepergian dengan rute memutar dari sana ke Inggris.
Kritikus Sissy Helff dari the Goethe-University Frankfurt, Jerman, pada sebuah telaah ilmiah pernah berpendapat bahwa By the Sea adalah contoh bagus dari konfrontasi pembaca dengan gambaran yang sangat kompleks. Yaitu, tentang kesulitan pengungsi setelah pergerakan dan migrasi.
Tak diayal, tema-tema migran membuat Gurnah lihai menangkap fenomena dari benua Afrika. Ia pun begitu fokus pada tema kemanusiaan sehingga menghasilkan karya novel yang memukau dunia.
Saya teringat dengan kasus-kasus maraknya migran dari Asia Tengah dan Afrika yang masif terjadi di Eropa Timur. Pada 26 Agustus 2017, saya pernah hadir sebagai peserta pada 2nd International Poetry Festival “Taburetka” di Monchegorsk, Murmansk Oblast, Rusia.
Saya menggunakan kereta Moskwa-Murmansk sehari sebelumnya. Ketika di beberapa titik stasiun persinggahan, intel dan polisi memeriksa dokumen saya. Mereka juga menanyakan tujuan perjalanan.
Memang, saat itu banyak migran sudah mencapai Ukraina dan Polandia. Barangkali kulit dan perawakan saya berbeda dengan mayoritas penumpang di atas kereta. Itu lumrah menjadi alasan untuk dicurigai oleh para petugas.
Meski demikian, saya pun tetap sampai ke Monchegorsk. Berpartisipasi sebagai peserta pada acara pembacaan puisi Taburetka di sana. Sebuah perjalanan yang sangat berkesan. Pengalaman itu membuat saya bisa ikut merasakan bagaimana Gurnah menghadirkan tema-tema migran dalam karya novelnya.
Bernyanyi dan bersukaria
Usai topik sastra, saya beralih ke topik musik. Remy pun sontak semangat. Sebagai seniman multitalenta, ia masih bernyanyi. Suaranya sangat khas dan serak-serak. Kami berbicara, mulai dari lagu-lagu karya legendaris The Tielman Brothers sampai lagu-lagu daerah Nusantara. O Ina Ni Keke dan Bolelebo memiliki irama dan ketukan musiknya sama,” ucap Remy.
O Ina Ni Keke ialah lagu daerah asal Sulawesi Utara sedangkan Bolelebo asal Nusa Tenggara Timur (NTT). “Akar notasinya sama bersumber dari lagu rakyat Portugis,” sambung Remy sembari perlahan-lahan mengingat-ingat lirik lagunya.
Tak berapa lama, Remy pun menyiuk dan menyanyikan sebait lagu Bolelebo. Saya mendengar secara seksama. Belum selesai bernyanyi, Remy buru-buru meminta air mineral untuk membasahi tenggorokannya yang sedikit kering.
Seekor burung tetiba saja memerap dan menghinggapi jendela di kamar Remy berbaring. Dari jendela nampak kali kecil, pepohonan pisang, dan lain-lain. Burung-burung selalu mengepak sayap dan mondar-mandiri.
Sejurus, Emmy masuk kembali membawakan secangkir kopi tubruk. Cocok sekali bagi saya sembari menemani Remy bersantai-santai di sore hari. Seusai meletakkan kopi di meja kecil, Emmy bergegas ke ruangan tamu.
Ia mengambil sebuah surat yang diantarkan Pak Pos, beberapa hari lalu. Pengirimnya ialah seorang dosen Bahasa Indonesia dari Yokohama, Jepang, Ai Takeshita. Isi pesan begitu pendek dan singkat.
Bunyinya ‘Saya menunggu karya Pak Remy berjudul Brower. Semangat ya!’ Begitu tulis Takeshita.
Remy mendengar secara seksama saat Emmy bacakan perlahan-lahan surat tersebut. "Ya, semua ide sudah ada di kepala. Tinggal menuliskannya. Tokoh Brower adalah sosok mantan tentara Belanda di Semarang. Ini dari kisah nyata," ujar Remy.
Keinginan keras Remy untuk merealisasikan novel tersebut memang berapi-api. Sayang, kondisinya memang belum memungkinkan. "Semoga bisa ya," timpal Emmy mengamini dan memberi semangat kepada sang suami tercinta.
Senja itu, Remy dan Emmy melebarkan senyum di pipi mereka. Seakan ada kenangan manis mengendap-endap di ingatan. Sepucuk surat dari ‘Negeri Sakura’ pun kian mendatangkan sekeping keceriaan. (SK-1)
Baca juga: Sajak-sajak Remy Sylado
Baca juga: Sajak-sajak Boris Pasternak
Baca juga: Sajak-sajak Yevgeny Yevtushenko
 Iwan Jaconiah adalah penyair, editor puisi Media Indonesia, dan penulis buku Hoi!, sebuah kumpulan puisi tentang kisah diaspora Indonesia di Rusia.
Iwan Jaconiah adalah penyair, editor puisi Media Indonesia, dan penulis buku Hoi!, sebuah kumpulan puisi tentang kisah diaspora Indonesia di Rusia.
Terkini Lainnya
Bernyanyi dan bersukaria
Totalitas Bradley Cooper Perankan Legenda Komposer Asal Amerika Serikat
Keluarga Bernstein Bela Keputusan Bradley Cooper Pakai Hidung Palsu di Film
Rekam Jejak Maestro Djoko Pekik dalam Arsip IVAA
Maestro Djoko Pekik Meninggal Dunia
Sajak-sajak Remy Sylado
6 Tokoh Penderita Albinisme Terkenal dan Mendunia
Salim Said di Mata Para Sahabat, Teladan untuk Generasi Muda
Tak Hanya RA Kartini, ini 2 Pahlawan Perempuan yang Bawa Perubahan di Indonesia
UAS Dukung Anies-Muhaimin, Timnas: Mengekspresikannya Perlu Waktu
Mengingat Penyair Intojo di Hari Puisi Sedunia
Kerja Sama BUMDes dan Antam Dinilai Sebagai Solusi 'Gurandil' di Gunung Pongkor
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap